 Bukan hal baru bila beras dijadikan instrumen politik dalam kampanye. Pada zaman baheula, pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Pangan menjadi instrumen paling ampuh untuk mewujudkan ambisi politik.
Bukan hal baru bila beras dijadikan instrumen politik dalam kampanye. Pada zaman baheula, pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Pangan menjadi instrumen paling ampuh untuk mewujudkan ambisi politik.Menjelang pemilu, instrumen purba itu kembali dipercayai bisa menyediakan tiket untuk meraih posisi penting melalui perolehan suara. Ini kasat mata dari iklan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengklaim kadernya berhasil meningkatkan produksi beras hingga mencapai swasembada pada 2008. Bahkan, pada 2009 diyakini akan ekspor beras.
Ekspor Beras
Perum Bulog, seperti pengakuan Direktur Utama Bulog Mustafa Abubakar kepada penulis, ditunjuk pemerintah sebagai pelaku ekspor. Yang diekspor bukan beras jenis medium tiga untuk raskin, tetapi beras aromatik. Jumlahnya cuma 100.000 ton. Ekspor akan dilakukan pada triwulan II atau III tahun ini. Dari sisi jumlah, rencana ekspor sebesar itu sebenarnya amat kecil, hanya 0,28 persen dari produksi beras 2008 (angka ramalan III BPS). Bagi petani, ekspor tak banyak faedahnya. Petani bukan eksportir. Lagi pula, beras aromatik hanya diproduksi segelintir petani. Mayoritas petani memproduksi beras non-aromatik.
Karena itu, ekspor beras hanya akan menguntungkan eksportir, dan—tentu saja—pemerintah. Dengan harga beras aromatik 1,5 dollar AS - 2,0 dollar AS per kg di Jepang, eksportir akan menangguk untung besar.
BAgi pemerintah yang berkuasa (incumbent), ekspor beras akan memoles citra, menaikkan elektabilitas dan akseptabilitas publik. Padahal ekspor baru rencana. Ekspor beras juga bukan barang baru bagi Indonesia. Tahun 2006, saat impor 0,84 juta ton, kita juga ekspor beras. Namun, saat itu tak ada yang melansir. Sebaliknya, kini ekspor beras jadi komoditas politik eksotik.
Pangan (baca: beras), secara harfiah bukan persoalan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, pangan diperlakukan sebagai bahan-bahan yang diperlukan jasmani agar badan manusia bisa bertahan hidup. Sebenarnya terlalu banyak unsur alami di bumi yang segera dapat dikelola untuk “sekadar” menjadi bahan pangan pengganjal perut lapar. Namun, disinilah pangkal persoalannya. Karena merupakan kebutuhan jasmani yang tak terelakkan yang—dalam istilah antropolog Melville J Herskovitas—merupakan the primary determinants of survival bagi umat manusia, pangan menjadi barang langka saat dihadapkan dengan sistem ekonomi dan politik yang lebih luas.
Pangan dan Politik
Hubungan pangan dan politik berangkat dari asumsi bahwa seluruh kehidupan manusia dapat secara dramatis direduksi hanya pada perburuan makanan. Lepas dari berbagai cara, gaya, kebiasaan, dan selera masing-masing kelompok masyarakat, kebutuhan pangan merupakan cara paling esensial untuk mempertahankan hidup. Pangan menjadi kebutuhan permanen yang tidak pernah hilang. Karena itu, kecukupan pangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pangan harus tersedia setiap saat dalam jumlah cukup, saat panen atau paceklik, dan dengan harga yang terjangkau siapa pun.
Fungsi pangan sebagai komoditas hajat hidup orang banyak inilah yang melahirkan unsur politik. Seseorang atau lembaga yang menguasai sumber-sumber pangan akan mempunyai posisi tawar dan posisi politik tertentu. Kekuatan tawar dan politik kian mekar manakala mereka juga menguasai organisasi pengolahan pangan, distribusi, sekaligus fasilitas-fasilitas publik dalam proses produksinya.
Kendali sumber pangan
Kendali atas sumber-sumber pangan berarti pengendalian politik publik secara keseluruhan. Sejauh sebuah rezim mampu mengendalikan sumber-sumber itu, menjaganya dari ancaman kelangkaan, dan menstabilkan harga di konstituen strategis, sejauh itu pula stabilitas politik akan mantap sekaligus meraih simpati luas.
Sebaliknya, kekuatan politik terguncang bila gagal menjaga stabilitas harga pangan. Inilah pesan yang hendak disampaikan Presiden Yudhoyono saat hadir di Perum Bulog. Bahkan, secara terbuka, SBY meminta Bulog menstabilkan harga gula dan minyak goreng (Kompas, 5/2).
Doktrin ini diyakini pemerintah di banyak negara berkembang dan miskin, termasuk Indonesia. Di negara-negara seperti itu, sebagian besar (60%) pendapatn warga terserap habis untuk membeli pangan. Dalam masyarakat politik, masalah pangan bisa menjadi ancaman stabilitas politik yang bersifat laten dan setiap saat bisa meledak. Ada banyak penyebab jatuhnya Soekarno dan Soeharto, tetapi satu hal tak terbantahkan, ketidakmampuan rezim mengendalikan pangan. Inilah alasan mengapa hingga kini pemerintah masih memperlakukan beras sebagai komoditas politik.
Sejauh ini politik beras itu cenderung merugikan produsen dan konsumen. Melalui inpres perberasan yang direvisi setiap tahun, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras. HPP bukan bentuk perlindungan harga. Batu pijak HPP adalah kuantitas untuk memenuhi stok nasional dan raskin. Karena sifatnya target kuantum, pengaruh pembelian pada tingkat harga di pasar jadi residual. Saat harga gabah anjlok atau harga beras tinggi, beleid HPP tak bisa jadi alat kendali harga. Akibatnya, dalam dua posisi itu, petani (produsen) dan konsumen merugi. Karena sama-sama tidak menguntungkan, politisasi beras harus diakhiri.
------------------------------------------------------------------------------
KHUDORI, Penulis Buku Ironi Negeri Beras (Insist Press, 2008);
Peminat masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi - KOMPAS
Resource: vgsiahaya
------------------------------------------------------------------------------
 Judul Buku : Ironi Negeri Beras
Judul Buku : Ironi Negeri BerasPenulis : Khudori
Penerbit : Insist Press, Yogyakarta
Cetakan : Juni, 2008
Tebal : xvi + 366 halaman
Resensi Oleh Wahyu Arifin
BERAS kini bukan hanya makanan pokok. Beras juga bisa menjadi komoditas politik berdimensi kompleks. Karena itu, pemerintah merasa perlu campur tangan dalam menjamin ketersediaan dan mengontrol harga beras. Namun sejarah mencatat kebijakan tentang beras selalu mengundang persoalan dan sering mengguncang rezim berkuasa seperti yang terjadi di Filipina dan Korea Selatan.
Di Indonesia, pada masa Presiden Soekarno pemerintah cenderung berkonsentrasi di dunia politik, sehingga gagal menerapkan kebijakan pangan dan Soekarno pun terjungkal. Pada masa Orde Baru, Soeharto mencoba menarik kembali kepercayaan publik dengan kebijakan pertanian yang lebih populis. Kebijakan itu dikenal dengan nama Revolusi Hijau yang menitikberatkan pada teknologi pertanian yang lebih modern.
Dulu kalkulasi perhitungan untung rugi atas pertanian dibuat dengan cara tawar-menawar dengan alam, kini berhubungan dengan kekuasaan negara dan kebutuhan modern yang digerakkan oleh industrialisasi. Bersamaan dengan itu, semua asupan harus dibayar oleh petani. Asupan produksi berupa bibit unggul, pupuk, dan pestisida harus dibeli petani pada toko-toko besar penyalur korporasi transnasional (TNC's).
Penerapan Revolusi Hijau yang mengharuskan pemakaian pupuk dan pestisida kimiawi secara besar-besaran menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Setelah tahun 1990 impor beras Indonesia kian melonjak. Dari tahun ke tahun jumlah impor beras cenderung tinggi, bahkan seperti ketagihan dan tak bisa dielakkan. Terjadi pertumbuhan produktivitas negatif yang disebabkan makin jenuhnya lahan terhadap teknologi, terutama yang berkaitan dengan asupan kimia (pupuk dan pestisida).
Wajah Petani Indonesia
"USAHA tani padi harus dilindungi!" teriak para petani Korea Selatan saat berunjuk rasa menentang liberalisasi pangan. Mereka percaya padi adalah identitas mereka sehingga harus dilindungi. Bahkan, saking menghormati identitasnya dan menolak liberalisasi pangan, Lee Kyung Hae, petani Korea Selatan, nekat bunuh diri pada saat pertemuan World Trade Organization di Cancun, Meksiko. Tak hanya di Korea Selatan yang petaninya menentang liberalisasi pangan. Para petani Indonesia juga tak putus-putus berunjuk rasa menentang liberalisasi pertanian.
Indonesia sejak 1998 telah didikte oleh International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional untuk menghapuskan semua instrumen pendukung pertanian. Di bawah supervisi IMF, Indonesia begitu cepat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pangan. Dalam perdagangan internasional, Indonesia mengikat perjanjian dengan WTO melalui AoA (perjanjian pertanian) yang artinya membuka pasar domestik untuk pangan impor.
WTO dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat mempermainkan negara-negara miskin, termasuk Indonesia. Mereka akan membuat negara-negara itu tergantung pada impor pangan dan kemudian menaikkan harga. Mereka menyuruh meliberalisasi pertanian, tetapi memberikan subsidi besar-besaran sektor pertanian mereka.
Karena tak ada proteksi dari pemerintah, petani Indonesia mudah dihantam berbagai masalah. Sebaliknya, petani negara-negara maju yang mengekspor bahan pangan ke Indonesia dilindungi dan disubsidi secara besar-besaran.
Tak heran bila kemudian para petani berunjuk rasa. Mereka jatuh miskin, kurang pangan, dan kelaparan. Akhirnya tercipta frustrasi massal. Jangan heran jika para petani nekat membakar gabah dan ladangnya karena sudah tak kuat menanggung derita.
Berpijak dari kenyataan tersebut, Khudori, penulis buku Ironi Negeri Beras, yakin jaminan perlindungan terhadap petani merupakan modal dasar kebangkitan bangsa ini. Menurut dia, kebijakan yang berpihak pada petani harus diimbangi dengan kebijakan redistribusi aset, yaitu lahan. Reforma agraria merupakan keharusan dan kebutuhan yang mendesak. Hal itu bukan hanya untuk mengangkat petani dari jurang kemiskinan, tapi juga menjamin kedaulatan pangan bangsa.(E6)
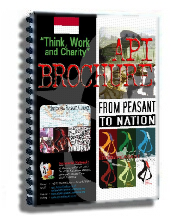
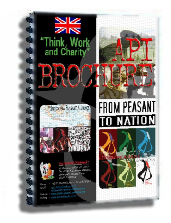
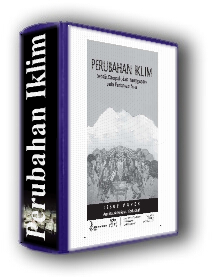
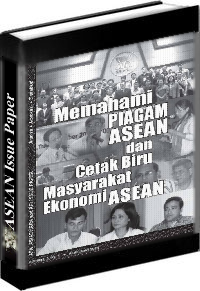
keren artikelnya gan. thank's.
www.kiostiket.com